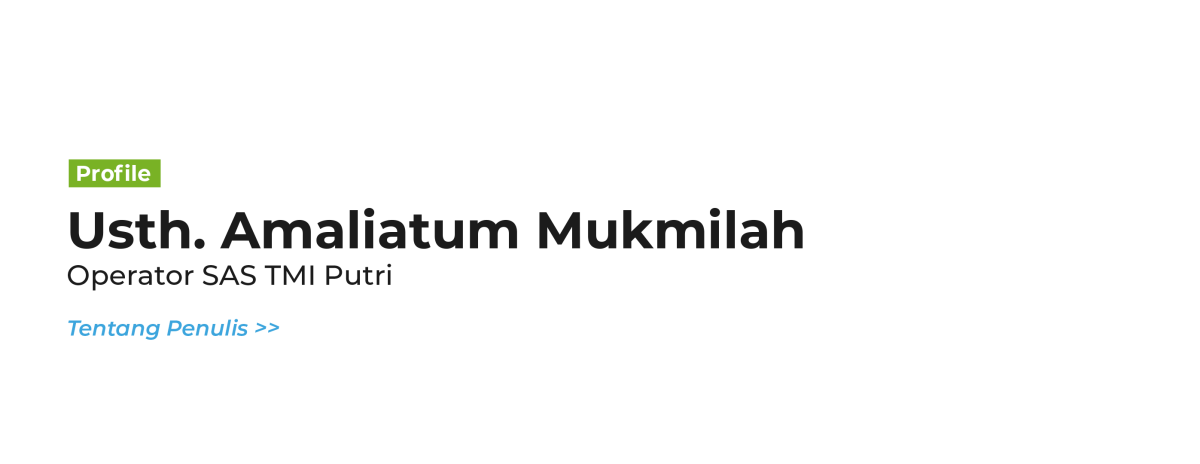Pesantren telah lama menjadi wajah khas Islam Nusantara. Disanalah ajaran Islam tidak hanya diajarkan secara tekstual, tetapi juga dihidupi dalam bentuk perilaku, etika, dan adab. Dari pesantren pula lahir banyak tokoh bangsa, ulama, dan intelektual yang memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. Namun, seiring perubahan zaman, tradisi pesantren menghadapi ujian—bagaimana menjaga nilai-nilai adab islami tanpa terjebak dalam feodalisme yang mengekang kebebasan berpikir. Dalam konteks inilah penting untuk membedah kembali nilai-nilai islami yang tumbuh dalam budaya pesantren, antara kearifan yang perlu dijaga dan tradisi yang perlu disaring.
Pesantren: Antara Tradisi dan Transformasi
Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia, bahkan sebelum berdirinya sistem sekolah formal. Ia lahir sebagai hasil dialektika antara ajaran Islam dengan budaya lokal nusantara. Hasani Ahmad Said (2011) dalam artikelnya “Meneguhkan Kembali Tradisi Pesantren di Nusantara” menjelaskan, bahwa sistem pesantren berakar pada model pendidikan asrama (biara) yang telah ada di masa hindu-buddha, kemudian diislamisasi oleh para ulama seperti Syaikh Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Ampel. Maka, pesantren tidak hanya merupakan lembaga keagamaan, melainkan juga lembaga sosial dan budaya.
Ciri utama pesantren bukan hanya pada pengajaran kitab kuning, tetapi pada nilai-nilai yang dihidupi para santri. Tradisi penghormatan kepada guru (kiai), hidup sederhana, mandiri, dan ikhlas menjadi identitas moral yang membentuk “subkultur pesantren.” Nilai-nilai ini menjadikan pesantren bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga tempat tazkiyatun nafs (penyucian jiwa). Dalam kehidupan yang serba materialistik, nilai-nilai ini adalah fase spiritual yang mengajarkan kesederhanaan dan keikhlasan.
Namun, sebagaimana setiap tradisi, pesantren tidak hidup di ruang hampa. Ia berinteraksi dengan dinamika sosial, modernisasi, dan globalisasi. Perubahan ini sering kali menimbulkan ketegangan antara mempertahankan tradisi dan menyesuaikan diri dengan zaman. Sebagian pihak menilai pesantren terlalu konservatif dan tertutup, sementara yang lain justru melihat pesantren sebagai benteng moral yang menjaga nilai-nilai Islam dari arus sekularisasi.
Adab Islami sebagai Ruh Pesantren
Kekuatan terbesar pesantren terletak pada adab. Dalam pandangan Islam, adab tidak sekadar sopan santun, tetapi tatanan moral dan spiritual yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Dalam pesantren, adab menjadi lebih penting daripada sekadar pengetahuan. Para santri diajarkan untuk menghormati kiai, mencintai ilmu, dan menjaga akhlak.
Zamakhsyari Dhofier (1990) mencatat, bahwa lima elemen dasar pesantren—kiai, santri, masjid, asrama, dan kitab kuning—berfungsi membangun sistem pendidikan berbasis moral. Kiai tidak hanya guru, tetapi figur spiritual yang menjadi teladan hidup. Relasi santri dan kiai dibangun atas dasar cinta, bukan kontrak formal. Dari sinilah lahir ungkapan populer di kalangan pesantren: “Ilmu yang tidak berkah adalah ilmu yang dipelajari tanpa adab.”
Adab santri kepada kiai mencerminkan nilai Islam tentang tawadhu’ (rendah hati) dan ta’dzim (penghormatan). Nilai ini tidak hanya memperkuat kedisiplinan moral, tetapi juga menjaga kesinambungan ilmu melalui sanad keilmuan yang bersambung hingga para ulama klasik. Seperti disebut Hasani, tradisi keilmuan pesantren menekankan kesinambungan sanad dan transmisi ilmu yang menjadi dasar otoritas keulamaan. Dengan adab, ilmu tidak hanya dipindahkan, tetapi diwariskan secara spiritual.
Namun, dalam praktiknya, adab kadang bergeser menjadi ketundukan mutlak. Relasi kiai-santri yang idealnya dibangun atas penghormatan bisa terjebak dalam relasi kuasa yang feodal. Ketika otoritas spiritual tidak diimbangi dengan kesadaran kritis, penghormatan dapat berubah menjadi kultus individu. Di sinilah perlu dibedakan antara adab sebagai nilai Islami dan feodalisme sebagai penyimpangan kultural.
Kearifan Lokal dalam Tradisi Pesantren
Salah satu kekhasan pesantren nusantara adalah kemampuannya menyerap nilai-nilai kearifan lokal. Pesantren tidak lahir dari ruang Timur Tengah, melainkan tumbuh di tanah Jawa, Sunda, Madura, Aceh, dan Minangkabau, masing-masing dengan tradisi lokal yang kuat. Kiai sebagai tokoh lokal berperan tidak hanya sebagai pengajar agama, tetapi juga sebagai mediator sosial dan penjaga harmoni masyarakat.
Tradisi gotong-royong, musyawarah, dan kehidupan sederhana di pesantren adalah warisan budaya nusantara yang diislamisasi. Dalam konteks ini, pesantren menjadi laboratorium harmonisasi antara nilai Islam universal dan budaya lokal. Santri diajarkan bahwa menjadi muslim yang baik bukan berarti meninggalkan budaya sendiri, tetapi memurnikan dan memperbaikinya.
Nilai-nilai ini sesuai dengan prinsip al-qadim al-shalih wal-jadid al-aslah, tradisi lama yang baik harus dijaga, dan yang baru yang lebih baik harus dikembangkan. Prinsip ini menjadi pedoman bagaimana pesantren menyeleksi modernitas; tidak menolak perubahan secara buta, tetapi menimbangnya dengan kebijaksanaan moral. Modernisasi pendidikan, penggunaan teknologi, bahkan pembaruan kurikulum dilakukan tanpa mengorbankan ruh adab.
Namun, kearifan lokal juga dapat berubah menjadi belenggu jika diterima tanpa kritik. Misalnya, budaya paternalistik di sebagian pesantren dapat memperkuat pola relasi “atas–bawah” yang kaku. Dalam situasi ini, nilai “hormat kepada guru” bisa disalahartikan sebagai “tidak boleh berbeda pendapat.” Padahal, Islam sendiri menempatkan musyawarah dan kebebasan berpikir sebagai bagian dari adab intelektual. Oleh karena itu, penyaringan tradisi menjadi keharusan agar kearifan tidak berubah menjadi kejumudan.
Antara Adab dan Feodalisme
Kritik terhadap pesantren sering diarahkan pada relasi kuasa antara kiai dan santri. Sebagian kalangan menilai pesantren memelihara kultur feodal: kiai ditempatkan di posisi “setengah suci,” sementara santri menjadi pihak yang tunduk tanpa daya kritis. Kritik ini muncul terutama di era modern ketika kebebasan berpikir dan kesetaraan menjadi nilai global.
Namun, penting membedakan antara feodalisme dan adab. Feodalisme lahir dari struktur sosial yang menindas: adab lahir dari kesadaran spiritual. Dalam adab, penghormatan muncul dari cinta dan keikhlasan, bukan karena paksaan atau hierarki sosial. Seorang santri mencium tangan kiai bukan karena ia budak, tetapi karena ia menghormati ilmunya.
Masalah muncul ketika struktur sosial di pesantren tidak mampu lagi membedakan batas antara spiritualitas dan kekuasaan. Ketika nasihat kiai dianggap hukum mutlak, atau ketika kritik dianggap sebagai dosa, maka adab telah tergantikan oleh feodalisme. Di titik inilah pentingnya pendidikan kritis dalam pesantren yang mengajarkan santri untuk tetap beradab sekaligus berpikir rasional.
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pernah mengingatkan bahwa pesantren harus terus “menggerakkan tradisi,” bukan sekadar “menjaganya.” Tradisi yang tidak bergerak akan menjadi beku dan kehilangan makna. Menggerakkan tradisi berarti membaca kembali warisan masa lalu dengan semangat zaman kini. Dengan demikian, penghormatan kepada kiai tidak berarti menutup ruang diskusi; dan kesetiaan pada tradisi tidak berarti menolak inovasi.
Pesantren di Era Modern: dari Kepatuhan ke Kemandirian
Kini pesantren telah memasuki fase baru. Banyak pesantren yang membuka sekolah formal, perguruan tinggi, bahkan menjalankan program pemberdayaan ekonomi. Transformasi ini menunjukkan bahwa pesantren mampu beradaptasi tanpa meninggalkan jati dirinya.
Namun, tantangan baru muncul; bagaimana menjaga ruh keikhlasan dan kesederhanaan di tengah modernisasi? Ketika pesantren mulai berinteraksi dengan sistem ekonomi dan politik, ada risiko nilai-nilai spiritualnya terkikis oleh kepentingan duniawi. Di sinilah pentingnya adab sebagai kompas moral.
Adab mengajarkan keseimbangan antara ilmu dan amal, antara intelektualitas dan moralitas. Dalam konteks pendidikan modern, pesantren bisa menjadi model pendidikan integratif; memadukan kecerdasan spiritual, emosional, dan sosial. Sistem pendidikan yang menumbuhkan karakter tawadhu’, tanggung jawab, dan kebersamaan adalah kontribusi besar pesantren bagi bangsa.
Di tengah krisis moral dan degradasi etika publik, pesantren justru menawarkan alternatif” pendidikan berbasis nilai. Dunia modern mungkin mengajarkan skill, tetapi pesantren mengajarkan hikmah kebijaksanaan dalam menggunakan ilmu untuk kebaikan.
Menjaga Adab, Menyaring Tradisi
Menjaga adab dan menyaring tradisi adalah dua tugas besar pesantren di abad ini. Menjaga adab berarti melestarikan ruh Islam yang menekankan akhlak, kasih sayang, dan penghormatan. Sementara menyaring tradisi berarti membersihkan unsur-unsur yang tidak lagi relevan atau bertentangan dengan nilai Islam yang universal.
Pesantren perlu terus menjadi ruang dialog antara masa lalu dan masa depan. Ia tidak boleh larut dalam romantisme masa lalu, tetapi juga tidak boleh kehilangan akar tradisinya. Modernisasi harus dijalankan dengan kesadaran spiritual, agar tidak merusak esensi pendidikan pesantren.
Jika adab menjadi pondasi, dan tradisi disaring dengan bijak, maka pesantren akan terus menjadi sumber cahaya peradaban. Dari bilik-bilik pesantren yang sederhana, nilai-nilai keikhlasan, kebersamaan, dan kearifan akan terus mengalir, menerangi nusantara yang sedang mencari arah moralnya.